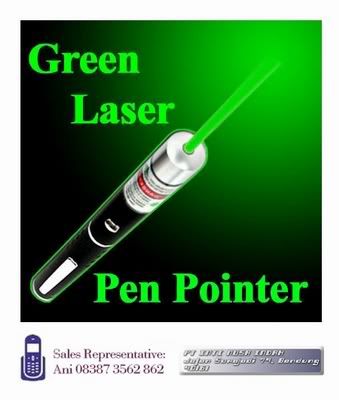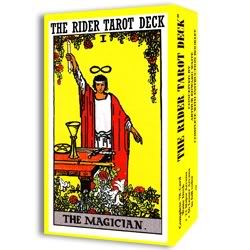Suatu
hari menjelang senja di Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh. Sebut saja nama
Ghafur. Ghafur adalah salah seorang Komandan Regu Wilayatul Hisbah (WH)
Kota Banda Aceh. Hari itu, bersama lima orang rekannya, Ghafur tengah
melakukan razia khalwat di pantai yang kerap dijadikan muda-mudi untuk
berbuat maksiat.
Dari jarak pandang yang relatif jauh. Ghafur melihat sebuah mobil
mencurigakan. Samar-samar ia melihat dua sejoli yang tengah memadu kasih
di dalam mobil itu. Untuk menghilangkan rasa penasaran, ia lalu
mengajak kelima rekannya mendekati mobil itu. Benar saja, di dalam mobil
tersebut ada yang tengah berkhalwat.
Ghafur lalu mengetuk kaca mobil tersebut. Saat perlahan-lahan kaca
mobil itu diturunkan, ia tak melihat sedikit pun guratan wajah bersalah
dari sepasang pelaku mesum itu. Justru Ghafur dibuat kaget. Ia
diperlihatkan senjata api sejenis revolver oleh lelaki yang berada di
dalam mobil.
“Ini (peluru) cukup untuk kalian ber-enam,” kata Ghafur menirukan perkataan lelaki itu.
Karena anggota WH tak dilengkapi senjata, maka Ghafur dan rekannya bergegas menjauhi mobil itu.
Pada fragmen lain, Mahyeddin Husra, warga Aceh, dibuat gusar ketika
melihat belasan pasangan muda-mudi tengah berkhalwat secara massal di
pinggiran Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Sabtu (4/6/2011) malam.
Bahkan ada sepasang pelaku mesum itu terlihat berani saling merangkul
dan menjamah anggota tubuh.
“Kalau begini, apa bedanya Aceh dengan Jakarta atau kota-kota lain?
Negeri yang bersyariat kok seperti ini?” kata Mahyeddin kepada Suara
Hidayatullah dengan suara lirih.
Tak tahan melihat kemungkaran di depan matanya, ia lalu menelepon
kenalannya yang bertugas sebagai anggota WH. Di ujung telepon sana bukan
respon baik yang diterima Mahyeddin, malah keluhan sang WH yang
diterimanya.
“Dia (anggota WH tadi -red) bilang WH sudah payah. Tak sanggup dengan
kondisi yang terbatas harus menertibkan pelaku maksiat yang semakin
banyak,” ujar Mahyeddin menirukan suara yang didengarnya di ujung
telepon.
Dari dua fragmen di atas terungkap sebuah fakta tentang
ketidakberdayaan WH mengawal syariat. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran
qanun, seperti berkhalwat, mudah sekali ditemukan di daerah yang
terkenal dengan sebutan Tanah Rencong itu.
Selain Pantai Ulee Lheue dan Lapangan Blang Padang, di sejumlah kedai
kopi di Banda Aceh juga mudah ditemukan muda-mudi yang berkhalwat.
Berdasarkan pengamatan Suara Hidayatullah, di jalan Soekarno-Hatta
terdapat kedai-kedai kopi beratap langit tanpa alat penerangan yang
sering dimanfaatkan untuk berbuat mesum.
Di jembatan Pante Pirak beda lagi. Jembatan yang hanya berjarak
ratusan meter dari Masjid Raya Baiturrahman itu setiap malam Ahad
berkumpul para anak baru gede (ABG). Bahkan di jembatan itu pernah
dijadikan tempat kumpul anak-anak Punk, atau berandalan.
Ketika Suara Hidayatullah melintas di atas jembatan Pante Pirak,
terlihat ada beberapa ABG perempuan yang tidak berjilbab. Mereka
bercengkerama dengan teman-teman lelakinya tanpa jarak. Meski di
sana-sini terjadi pelanggaran qanun, tetapi tidak terlihat petugas WH
berpatroli.
Minim Dukungan
Keterbatasan yang dimiliki WH sudah menjadi rahasia umum di kalangan
masyarakat Aceh. Kekurangan personil hingga pada persoalan minimnya
anggaran operasional merupakan dinamika yang terjadi dalam pasukan
pengawal syariat ini.
Komandan Operasional WH Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),
Teungku Adin mengatakan selama ini WH tidak mendapat dukungan penuh dari
lembaga legislatif dan eksekutif. “Tidak ada dukungan dari para pihak
yang membentuk WH. Termasuk dukungan fasilitas dan dana,” kata Adin
saat ditemui Suara Hidayatullah di Kantor WH Provinsi NAD, Jalan T Nyak
Arief Jambo Tape, Banda Aceh.
Adin mengaku, anggota WH sering terlibat bentrokan dengan oknum yang
mengaku aparat saat melakukan penertiban. Sampai saat ini, kata Adin,
belum ada anggota polisi ataupun tentara pelanggar qanun yang berhasil
diproses hingga ke Mahkamah Sar’iyah (MS). Sehingga ada kesan jika qanun
itu hanya berlaku bagi masyarakat sipil.
Belum Dieksekusi
Menurut data Mahkamah Sar’iyah Provinsi Aceh, kasus judi atau maisir
menjadi jumlah terbanyak dalam perkara jinayat dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2010 kasus judi yang tercatat dan masuk ke MS sebanyak 102 kasus.
Sementara urutan kedua dan ketiga adalah kasus khalwat dengan 25 kasus
dan khamar dengan 8 kasus.
Wakil Ketua MS Provinsi Aceh, Armia Ibrahim, SH, mengungkapkan
angka-angka kasus di atas tidak semuanya tuntas sampai proses eksekusi.
Tercatat sejak tahun 2005 sampai Oktober 2010 setidaknya ada 103 kasus
jinayat yang belum dieksekusi (lihat tabel).
Penyebabnya, kata Armia, karena terdakwa sudah tidak ada di tempat.
Pelaku tidak dapat ditahan, sehingga dengan leluasa melarikan diri.
Selama ini pelaku pelanggar qanun tidak bisa ditahan (dipenjara) sampai
vonis jatuh, karena memang belum ada aturan yang membolehkannya.
Seharusnya, jelas Armia, Qanun Hukum Acara Jinayat yang saat ini
tertahan di tangan gubernur segera disahkan. Qanun yang sudah disahkan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhir 2009 lalu ini mengatur
dibolehkannya penahanan pelaku.
Penyebab lainnya adalah persoalan teknis. Pihak eksekutor, dalam hal
ini kejaksaan, masih berpikir sempit terkait tata laksana eksekusi.
“Mereka masih berpikir jika proses eksekusi harus menggunakan
panggung, menyediakan konsumsi, dan honor untuk tim eksekutor. Malah,
awal-awal dulu mereka yang menerima hukuman cambuk diberi uang dan kain
sarung. Hal inilah yang membuat biaya jadi membengkak,” jelas Armia
kepada Ibnu Syafaat dari Suara Hidayatullah awal Juni lalu di Banda
Aceh.
Padahal, lanjut Armia, pelaksanaan eksekusi tidak harus seperti itu.
Sederhana saja, asal memenuhi Peraturan Gubernur tahun 2005.
Tidak Berwibawa
Tidak bertajinya lembaga yang berperan sebagai ujung tombak penegakan
syariat Islam, seperti WH dan Kejaksaan membuat banyak kasus-kasus
pelanggaran qanun tidak ditindak. Kalaupun ditindak, jarang yang sampai
ke proses eksekusi. Efeknya, kata Armia, wibawa hukum menjadi berkurang.
“Masyarakat bakal melihatnya seperti main-main. Ini bahkan bisa menjatuhkan penegak hukum karena kurang tegas,” ujar Armia.
Lemahnya lembaga eksekutor qanun ini juga dirasakan Teungku Muslim
Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. “Sebaik-baiknya
aturan, kalau tidak ada eksekutor maka percuma saja. Jadi persoalan
eksekutor inilah yang saat ini masih kurang,” jelas Muslim.
Polisi Syariat
Untuk menuju terciptanya lembaga penegak hukum yang kuat dan berwibawa,
TAF Haikal, Ketua Dewan Perwakilan Anggota Forum LSM Aceh mengusulkan
agar Pemerintah Aceh melakukan gebrakan, seperti pembentukan polisi
syariat.
Menurut Haikal, sebagai provinsi istimewa, Aceh memiliki
perbedaan-perbedaan yang tidak dimiliki provinsi lain. “Kalau di daerah
lain MUI (Majelis Ulama Indonesia -red), maka di Aceh disebut MPU. Kalau
di provinsi lain DPRD, maka di Aceh disebut DPRA. Begitu juga dengan
polisi. Kalau di daerah lain Polri, maka seharusnya di Aceh itu ada
polisi syariat,” papar Haikal.
Polisi syariat yang dimaksud Haikal adalah polisi yang menggantikan
peran Polri. Polisi yang dilengkapi persenjataan seperti halnya Polri.
Sementara, untuk mensiasati belum terbitnya Qanun Hukum Acara
Jinayat, Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Syariat Islam Dinas
Syariat Provinsi NAD, Syukri Muhammad Yusuf, menawarkan jalan keluar.
“Karena belum ada aturan yang membolehkan penahanan pelaku, maka jalan
keluarnya adalah sidang kilat. Cukup sehari. Misalnya pagi tertangkap
tangan melanggar qanun, siang hadirkan hakim dan jaksa. Kemudian sore
dieksekusi,” ujar Syukri. * SUARA HIDAYATULLAH, JULI 2011
















































 Jenis
senjata tradisional tombak juga termasuk salah satu senjata yang sering dipakai
oleh beberapa suku bangsa di nusantara termasuk suku Jawa. Bahkan munculnya
senjata tombak ini dimungkinkan sekali muncul pada zaman pra sejarah. Banyak
bukti ditemukan oleh para antropolog dan arkeolog baik yang berupa mata tombak
atau pun di relief-relief candi. Walaupun dalam perkembangan bentuk tombak
selalu berubah-ubah sesuai dengan pencipta suatu peradaban.
Jenis
senjata tradisional tombak juga termasuk salah satu senjata yang sering dipakai
oleh beberapa suku bangsa di nusantara termasuk suku Jawa. Bahkan munculnya
senjata tombak ini dimungkinkan sekali muncul pada zaman pra sejarah. Banyak
bukti ditemukan oleh para antropolog dan arkeolog baik yang berupa mata tombak
atau pun di relief-relief candi. Walaupun dalam perkembangan bentuk tombak
selalu berubah-ubah sesuai dengan pencipta suatu peradaban.